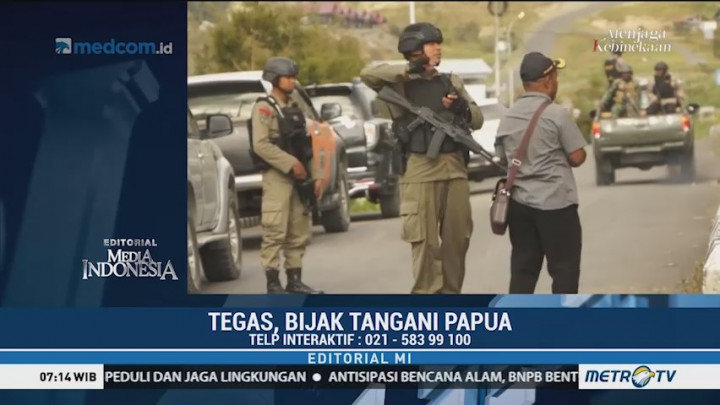PEMBICARAAN tentang pemilihan umum kepala daerah kembali menghangat. Pemicunya, segera disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Kada pada pertengahan September 2014 ini, yang amat mungkin mengubah mekanisme pemilu kada kabupaten/kota dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih DPRD.
Jalan menuju kembalinya pemilu kada ke tangan wakil rakyat kian lempeng setelah Fraksi Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, dan PPP berbalik arah di 'tikungan terakhir'. Para pemilik mayoritas kursi di parlemen itu tadinya ngotot mempertahankan pemilu kada langsung.
Sebagian masyarakat tentu sah mencurigai langkah balik badan parpol-parpol itu sebagai manuver politik kalkulatif ketimbang upaya menimbang demi kemaslahatan masyarakat. Itu karena perubahan sikap drastis tersebut hanya ditentukan dalam hitungan hari.
Namun, secara objektif harus kita katakan bahwa ide mengembalikan pemilu kada ke tangan DPRD amat masuk akal dan patut didukung. Selama ini, pemilu kada langsung sungguh menjadi ajang pesta, baik pesta demokrasi maupun pesta duit yang mengalir sampai jauh.
Calon kepala daerah menggelontorkan pundi-pundi ke pengusaha spanduk, rakyat pemilih, konsultan politik, bahkan mungkin ke penyelenggara pemilu yang berpihak. Ongkos politik pemilu kada pun membengkak.
Setidaknya ada empat pos pembiayaan yang sangat menguras energi peserta pemilu kada langsung, yakni biaya mahar partai politik, biaya menggerakkan mesin partai dan tim pemenangan, biaya kampanye, biaya
saksi di TPS pada saat pemilihan dan penghitungan suara, dan biaya penyelesaian kasus hukum di Mahkamah Konstitusi.
Beberapa pasangan calon kepala daerah, misalnya, mengaku menghabiskan Rp20 miliar hingga Rp128 miliar untuk bisa memenangi pemilu kada. Jika dikalkulasikan ada 3-5 pasang calon yang maju, bisa dihitung berapa biaya pemilu kada langsung yang harus dikeluarkan bila dikalikan dengan 505 kabupaten/kota di Indonesia? Belum lagi dana APBD untuk penyelenggaraan pemilu kada yang berkisar 4%-10% dari APBD.
Ongkos sosial yang harus ditebus juga mahal, yakni konflik horizontal antarpendukung. Akibatnya, pilihan bagi calon kepala daerah hanya satu, menang dengan apa pun caranya. Mereka tidak sudi kalah.
Pihak yang kalah berlomba-lomba menggugat melalui pengadil terakhir di MK. Pihak yang dinyatakan menang oleh KPU daerah pun mempertahankan mati-matian kemenangan mereka.
Putusan MK yang bersifat final dan mengikat menggoda banyak calon kepala daerah untuk jorjoran pada setiap persidangan, dari membayar pengacara kelas kakap sampai mengirim demonstran di depan gedung saat persidangan berlangsung.
Belum puas juga, pihak-pihak yang beperkara juga mencoba menebar duit ke hakim konstitusi. Bahkan, Akil Mochtar yang saat itu menjadi Ketua MK pun goyah dengan godaan fulus.
Benteng terakhir pengadilan pemilu tidak saja telah koyak, tapi juga roboh berkeping-keping. Demokrasi langsung, yang awalnya diniatkan untuk mengukuhkan kedaulatan rakyat, berbelok arah menjadi mesin perusak.
Substansi demokrasi pada hakikatnya akan tetap terjaga dengan pemilu kada oleh DPRD. Toh, penyelenggara pemilu tetap KPU dengan pengawasan oleh Panwaslu.
Konflik horizontal dapat dicegah, praktik korupsi juga bisa diminimalisasi, dan negara pun bisa mengalihkan hasil penghematan anggaran pemilu kada untuk dana kesejahteraan rakyat.
Menata Pemilu Kada
06 September 2014 06:40
VIDEO TERKAIT
VIDEO EDITORIAL MI VIDEO LAINNYA
MORE
POPULAR VIDEO